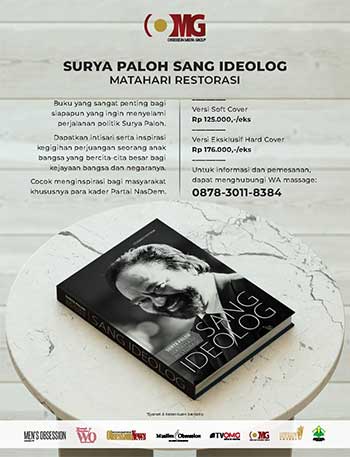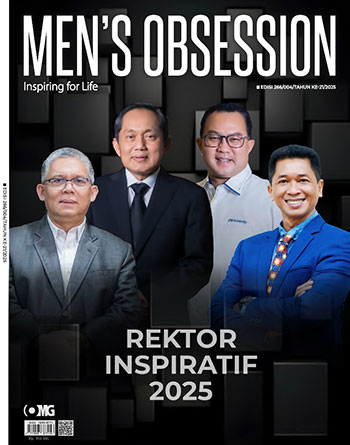Investasi Terbaik di Era AI: Manusia

Obsessionnews.com - Oleh : Dr.Aswin Rivai,SE.,MM
Salah satu sahabat saya yang berprofesi sebagai advokat baru-baru ini bercerita bahwa ia menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk mencatat hasil diskusinya dengan klien dan menyusun rangkumannya dan membandingkannya dengan kasus sejenis di masa lalu sehingga diperoleh rangkuman yang akurat. Dengan bantuan AI, ia menghemat waktu lebih dari 4 jam setiap harinya. Ketika saya bertanya bagaimana ia menggunakan waktu itu, ia menjawab sederhana namun inspiratif dengan mengatakan bahwa dia kini bisa berbicara lebih lama dengan kliennya yang sangat banyak. Dia merasa dirinya menjadi lebih produktif dari sebelumnya
Kisah sederhana itu mencerminkan inti dari transformasi digital yang seharusnya terjadi di setiap organisasi yaitu teknologi seharusnya membebaskan manusia untuk menjadi lebih manusiawi. Bukan menggantikan peran manusia, melainkan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan seperti empati, komunikasi, dan kolaborasi.
Perkembangan teknologi, terutama AI generatif, kini mengubah cara kerja di semua sektor. Laporan McKinsey (2024) memperkirakan bahwa sekitar 30% aktivitas kerja di Asia Tenggara dapat terotomatisasi pada 2030, termasuk di Indonesia. Artinya, sekitar 20 juta pekerja Indonesia perlu meningkatkan atau menyesuaikan keterampilannya agar tidak tertinggal.
Namun, digitalisasi tidak hanya tentang menguasai perangkat lunak atau coding. Yang paling penting adalah bagaimana manusia memanfaatkan teknologi untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dengan berpikir kritis, berempati, dan berkomunikasi dengan lebih efektif.
Program digital upskilling, atau peningkatan keterampilan digital, kini menjadi kebutuhan mendesak, bukan pilihan. Survei Kementerian Kominfo tahun 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 60% pekerja Indonesia merasa tidak memiliki keterampilan digital yang cukup untuk menghadapi perubahan teknologi.
Di sisi lain, hanya sekitar 25% perusahaan besar di Indonesia yang memiliki program pelatihan digital berkelanjutan untuk seluruh karyawannya. Padahal, perusahaan yang berinvestasi dalam pengembangan SDM digital terbukti lebih produktif 2–3 kali lipat dibanding yang tidak.
Beberapa perusahaan di Indonesia mulai memahami pentingnya transformasi manusia di tengah revolusi teknologi ini.
Bank Mandiri, misalnya, mengembangkan Mandiri Digital Academy, program internal untuk melatih ribuan karyawan dalam bidang data analytics, cyber security, dan AI. Mereka tidak hanya fokus pada teknologi, tetapi juga pada keterampilan komunikasi dan kolaborasi antartim.
Telkom Indonesia memiliki DigiTalent School, yang melatih pegawai dan masyarakat umum dalam literasi digital dan manajemen perubahan. Program ini bahkan membuka kelas bagi UMKM untuk memahami penggunaan AI sederhana dalam pemasaran dan analisis pelanggan.
Sementara itu, perusahaan ritel seperti Alfamart memanfaatkan AI untuk memprediksi permintaan barang dan mengatur distribusi logistik secara real-time. Namun mereka tetap menekankan pelatihan bagi staf toko agar dapat memberikan layanan lebih personal kepada pelanggan—membuktikan bahwa efisiensi digital tidak harus menghapus sentuhan manusia.
Meski ada kemajuan, jurang keterampilan digital (digital skill gap) masih lebar di Indonesia. Data World Economic Forum (2024) menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat ke-71 dari 100 negara dalam kesiapan tenaga kerja digital. Sebagian besar pekerja di sektor manufaktur, perdagangan, dan pertanian masih bekerja dengan pola tradisional tanpa pemanfaatan teknologi digital dasar.
Akibatnya, banyak perusahaan menghadapi paradoks yaitu mereka ingin bertransformasi digital, tetapi tenaga kerja mereka belum siap. Di sisi lain, banyak anak muda melek teknologi yang sulit menembus pasar kerja karena perusahaan belum siap beradaptasi dengan model kerja digital yang lebih fleksibel.
Perubahan cepat ini menuntut pergeseran budaya kerja—dari pola pikir “tahu segalanya”(know it all) menuju “ingin belajar segalanya”(learn it all). Konsep yang diperkenalkan CEO Microsoft Satya Nadella ini seharusnya menjadi fondasi transformasi di perusahaan-perusahaan Indonesia.
Namun survei PwC (2024) terhadap 120 CEO di Indonesia menunjukkan bahwa hanya 29% yang menjadikan budaya pembelajaran berkelanjutan sebagai prioritas utama.. Sebaliknya, lebih dari 80% menyebut investasi teknologi sebagai fokus utama, tanpa menyeimbangkannya dengan investasi pada manusia. Padahal, AI dan teknologi canggih hanya sekuat manusia yang menggunakannya.
Program peningkatan keterampilan yang efektif tidak bisa lagi bersifat seragam atau akademis. Harus ada pendekatan yang personal dan kontekstual, dengan kombinasi antara pelatihan formal, pembimbingan (mentoring), proyek nyata, dan rotasi kerja.
Perusahaan perlu memberi ruang bagi karyawan untuk mengelola perjalanan belajar mereka sendiri, dengan dukungan data dan teknologi yang relevan.
Peran Pemerintah dan Dunia Pendidikan
Pemerintah Indonesia sebenarnya telah meluncurkan berbagai inisiatif seperti Digital Talent Scholarship (DTS) dan Gerakan Nasional Literasi Digital, namun dampaknya belum merata.
Sebagian besar peserta berasal dari kota besar, sementara daerah-daerah dengan infrastruktur internet terbatas belum terjangkau.
Agar transformasi digital menjadi inklusif, pemerintah harus memperluas akses pendidikan digital hingga ke tingkat daerah melalui SMK, balai latihan kerja (BLK), dan universitas vokasi. Insentif pajak bagi perusahaan yang mengadakan program pelatihan digital bagi karyawan juga bisa menjadi stimulus kuat.
Selain itu, kurikulum pendidikan nasional harus bertransformasi dari sekadar penguasaan pengetahuan menuju pembentukan karakter digital yang adaptif dan etis—mengajarkan anak muda berpikir kritis, menggunakan AI secara bertanggung jawab, dan berkolaborasi lintas disiplin.
Peningkatan keterampilan digital bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau perusahaan.
Masyarakat, terutama generasi muda, harus menyadari bahwa kemampuan belajar ulang (relearning) dan belajar cepat (reskilling) kini menjadi kompetensi utama di pasar kerja.
Platform daring seperti Coursera, Dicoding, RevoU, dan Kampus Merdeka Digital menyediakan ribuan kursus yang bisa diakses dengan biaya rendah, bahkan gratis.
Namun, semangat belajar mandiri harus disertai dengan kesadaran bahwa teknologi hanyalah alat—yang paling menentukan tetaplah nilai kemanusiaan: empati, integritas, dan kemampuan beradaptasi
Para pemimpin organisasi juga harus menjalani perjalanan belajar mereka sendiri.
Mereka tidak hanya perlu memahami teknologi, tetapi juga harus mampu menjadi pemimpin yang inspiratif dan empatik. Pemimpin masa depan adalah mereka yang bisa memadukan kecakapan digital dengan kedalaman emosional.
Artinya, seorang direktur tidak cukup memahami AI, tetapi harus tahu bagaimana menggunakannya untuk membuat tim lebih kreatif dan bahagia.
Pemimpin yang sukses di era ini bukan yang paling pintar secara teknis, tetapi yang paling cepat belajar dan paling mampu membuat orang lain berkembang.
Kemajuan AI akan terus membentuk ulang dunia kerja dan cara kita belajar. Namun satu prinsip harus tetap dijaga: teknologi tidak boleh mengalahkan kemanusiaan.
Perusahaan yang berhasil di masa depan bukanlah yang paling cepat membeli teknologi, tetapi yang paling cepat menumbuhkan manusianya. Pemerintah yang berhasil bukan yang paling banyak membuat program digital, tetapi yang paling mampu membuka akses dan menumbuhkan semangat belajar rakyatnya.
Dan masyarakat yang siap menghadapi masa depan adalah mereka yang sadar bahwa menjadi digital berarti juga menjadi lebih manusia.
Era AI bukan sekadar revolusi teknologi tetapi ini adalah revolusi kemanusiaan.
Jika Indonesia ingin memanfaatkan potensi ekonomi digital yang diperkirakan mencapai USD 360 miliar pada tahun 2030 (sumber: Google-Temasek e-Conomy Report 2024), maka peningkatan keterampilan digital harus menjadi gerakan nasional.
AI bisa menulis kode, menganalisis data, dan mengoptimalkan proses. Namun hanya manusia yang bisa berpikir, merasa, dan bermakna. Menjadi digital berarti bukan kehilangan sisi manusia, tetapi justru menemukannya kembali. (Ali)