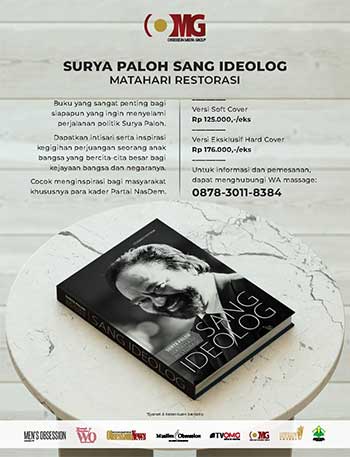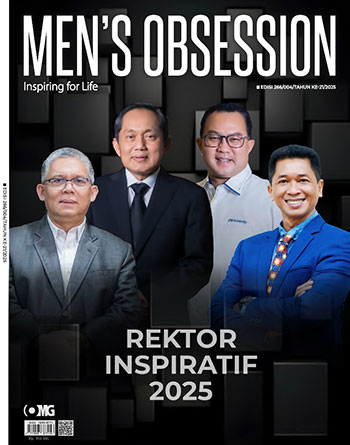Etika Pancasila dan Pagar Demokrasi

Oleh: Dr. Yoseph Umarhadi, Direktur Institut Filsafat Pancasila Artikel Ibu Megawati yang diterbitkan Harian Kompas pada 8 April 2024 menarik untuk dicermati dan direfleksikan kembali sebagai upaya mencari kebenaran. Artikel itu memberikan bahan renungan atau titik pijak kembali untuk merefleksikan bukan saja perjalanan demokrasi Indonesia pasca-reformasi, tetapi juga episode-episode sebelumnya. Sesuatu yang sudah sering dikerjakan, tetapi harus lebih sering dilakukan agar setiap warga negara memahami di mana kita berada saat ini, dan hendak ke mana kita menuju. Ada dua hal pokok yang layak mendapatkan perhatian lebih dari artikel yang ditulis oleh Ibu Megawati. Pertama, pentingnya keadilan dalam kehidupan bernegara. Pentingnya keadilan itu karena Bangsa Indonesia, meminjam ungkapan Moh. Yamin, merupakan hasil dialektika dalam menghadapi penjajahan atau kolonialisme yang eksploitatif dan menindas. Penjajah menghisap bukan saja tenaga rakyat Indonesia, tetapi juga sumber daya alam hingga tinggal menyisakan kemiskinan dan kesengsaraan. Pancasilanya yang merupakan hasil dialektika itu adalah jawaban atas kolonialisme dan imperialisme sebagaimana dikemukakan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Kedua, pentingnya etika dan keteladanan bagi para penyelenggara negara. Meskipun artikel itu ditujukan untuk memberikan saran bagi hakim Mahkamah Konstitusi, tetapi banyak pihak termasuk para guru besar menyuarakan pentingnya etika ini. Dengan kata lain, ada kemunduran etika di antara para penyelenggara negara. Lemahnya etika ini telah membuat para penyelenggara negara baik di sektor eksekutirf, legislatif, dan yudikatif tidak segan dan malu dalam menggunakan kekuasaan yang dimiliki demi kepentingan pribadi dan kelompoknya. Ini sungguh menggelisahkan. Karenanya, menjadi sangat tepat ketika Ibu Megawati mengatakan dalam artikel itu, ”Tanpa landasan etika, moral, dan keteladanan pemimpin, manipulasi hukum menjadi semakin mudah dilakukan.” Ini sudah terjadi, dan sebenarnya bukan saja putusah Mahkamah Konstitusi yang berdampak pada perubahan norma undang-undang dalam kasus capres-cawapres, tetapi juga dalam kasus lain seperti pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Artikel ini berusaha mempertajam refleksi Ibu Megawati Soekarno Putri tersebut dengan mempertajam dua isu pokok itu. Utamanya, etika keadilan Pancasila yang telah disinggung dalam artikel itu, tetapi belum mendapatkan uraian yang memadai. Namun, sebelum mengerjakan hal itu, ada baiknya kita diskusikan terlebih dahulu gagasan Steven Levitsky dan Daniel Ziblat (2019) dalam karya mereka yang banyak dibaca orang, Bagaimana Demokrasi Mati. Pagar Demokrasi Ide pagar demokrasi dikupas dalam bagian kelima buku Steven Levitsky dan Daniel Ziblat. Pada bagian itu, mereka mengatakan bahwa konstitusi merupakan dasar penting bagi demokrasi dan keberlangsungan suatu negara seperti Amerika Serikat. Namun, konstitusi bukanlah satu-satunya hal. Bagaimanapun Konstitusi selalu mempunyai kekurangan, dan konstitusi senantiasa multitafsir. Oleh karena itu, meskipun suatu konstitusi negara dirancang dengan sangat baik, oleh para hukum tata negara yang mumpuni, tetapi senantiasa ada kemungkinan gagal. Indonesia kiranya menjadi salah satu contoh yang baik. Sepanjang Indonesia merdeka, Indonesia telah mengalami pergantian beberapa konstitusi. Namun, Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen telah ditafsir secara berbeda dalam masa yang berbeda. Era Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto bersandar pada konstitusi yang sama, UUD 1945, tetapi keduanya hampir sama sekali berbeda dalam menafsirkannya. Lantas, jika konstitusi bukan satu-satunya jaminan untuk demokrasi dan kelangsungan hidup suatu negara, maka apa yang dapat menjamin hal itu? Menurut Steven Levitsky dan Daniel Ziblat, prasyarat itu adalah hukum tidak tertulis atau norma bersama. Aturan atau norma itulah yang menjadi pagar lembut demokrasi, yang mencegah persaingan politik harian merosot menjadi konflik tanpa aturan. Norma itu tidak bisa mengandalkan sifat baik pemimpin, melainkan berupa kode etik bersama yang diterima, dihormati, dan ditegakkan oleh anggota-anggotanya. Ada dua etika yang penting dalam hal ini, yakni saling toleransi dan menahan diri secara kelembagaan. Saling toleransi merujuk pada gagasan bahwa kita akan menerima para pesaing untuk memiliki hak hidup, memperjuangkan kekuasaan dan juga memerintah sejauh bermain sesuai aturan hukum dan konstitusi. Ketika lawan bermain sesuai dengan konstitusi dan hukum, maka akan menimbulkan keyakinan bahwa para pesaing bukanlah musuh. Ini karena ketaatan pada aturan main menciptakan trust kepada setiap orang atau pesaing lainnya bahwa para pesaingnya adalah seorang patriot, warga negara yang baik, dan tidak akan menggunakan hukum demi kepentingan mereka sendiri. Norma saling toleransi ini sangat penting karena tanpa itu persaingan akan menciptakan permusuhan. Ini yang tampaknya terjadi, terutama sejak keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pencalonan presiden dan wakil presiden. Norma kedua yang tidak kalah pentingnya yang dikemukakan Steven Levitsky dan Daniel Ziblat adalah sikap menahan diri secara kelembagaan. ”Sikap menahan diri” berarti pengendalian diri yang sabar, legawa, dan toleran atau ” tindakan tidak menggunakan suatu hak legal”. Secara implementatif, sikap ini berhubungan dengan untuk tidak melakukan tindakan hukum yang sah, tetapi melawan spirit hukum itu sendiri. Dengan begitu, para politikus tidak akan menggunakan seluruh kewenangan kelembagaan mereka meskipun mempunyai hak legal untuk melakukannya. Ini pada akhirnya akan menciptakan trust di antara para pesaing politik. Sayangnya, jika kita cermati, kedua norma ini tidak terjadi dalam proses politik pemilu 2024. Ketiadaan kehendak untuk menahan diri secara kelembagaan, mengurangi kurangnya saling toleransi. (Etika) Keadilan dalam Pancasila Adil atau kata jadiannya keadilan disebutkan dua kali dalam Pancasila. Adil yang pertama berada dalam konteks kemanusiaan. Artinya, bahwa kita harus adil dalam memandang manusia. Adil berarti menempatkan manusia sebagai subjek bukan objek. Jadi, dalam memandang dan berhubungan dengan sesama manusia, haruslah bersandar pada keadilan dan keadaban. Sementara itu, keadilan merujuk pada sifat. Bahwa sesuatu itu haruslah mempunyai sifat-sifat adil. Pada yang kedua ini, yang melekat pada sila kelima, adalah orientasi karena keadilan dilekatkan dalam ”keadilan sosial”. Oleh para penggagas Pancasila seperti Notonagoro, demokrasi Pancasila itu berdimensi ganda, yakni keadilan ekonomi dan keadilan politik. Oleh karena itu, setiap penyelenggara negara hendaknya dalam setiap tindakannya senantiasa memperhatikan dua dimensi keadilan ini. Dengan begitu, penyalahgunaan kekuasaan, kecurangan dalam pemilu, penggunaan hak legal formal secara penuh mungkin tidak akan digunakan jika berpotensi melanggar keadilan itu. Adil dalam hal ini dapat dimaknai sebagai tidak berat sebelah, tidak memihak, berpegang pada kebenaran atau tidak sewenang-wenang. Pemahaman adil yang demikian kiranya dapat menjadi pegangan bagi setiap penyelenggara negara ketika hendak memutuskan sesuatu, baik yang kecil (berdampak pada sedikit orang) atau keputusan besar (berdampak pada banyak orang). []