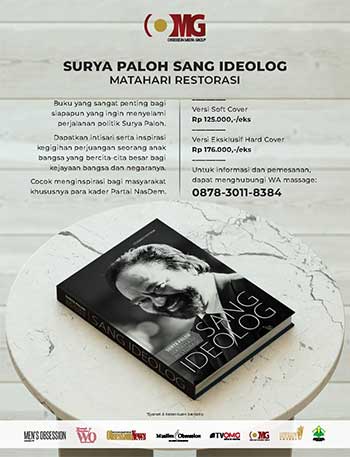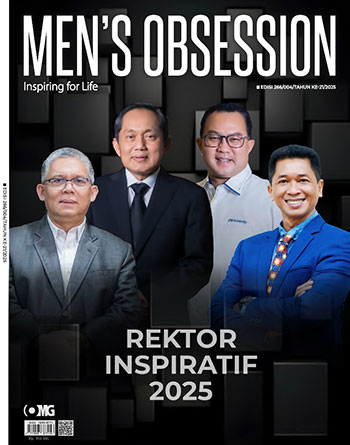Laporan “Mining &Money”: Dana Raksasa Global untuk Tambang Mineral Transisi Ikut Picu Krisis Lingkungan dan HAM di Indonesia

Obsessionnews.com —Sebuah laporan terbaru dari Koalisi Forests &Finance bersama jaringan masyarakat sipil internasional mengguncang wacana transisi energi global. Laporan berjudul “Mining and Money: Financial Fault Lines in the Energy Transition” itu mengungkap fakta mencengangkan: antara 2016 hingga 2024, bank-bank besar dunia telah menggelontorkan dana senilai USD 493 miliar dalam bentuk pinjaman dan penjaminan bagi perusahaan tambang mineral transisi. Sementara itu, para investor mengucurkan tambahan USD 289 miliar dalam bentuk obligasi dan saham per Juni 2025.
Mineral transisi seperti kobalt, nikel, litium, dan tembaga selama ini dipromosikan sebagai pilar penting dalam percepatan energi bersih. Namun, laporan tersebut justru menyoroti sisi gelap di balik kilau “energi hijau”. Pinjaman dan investasi itu dinilai memperkuat model pertambangan yang masih sarat masalah: deforestasi, pencemaran, perampasan tanah masyarakat adat, pelanggaran hak-hak pekerja, hingga tragedi runtuhnya bendungan dan bocornya limbah beracun yang menghancurkan ekosistem serta kehidupan masyarakat lokal.
“Meski dikampanyekan sebagai bagian dari transisi energi, praktik penambangan dan pembiayaan mineral transisi masih jauh dari bersih, hijau, atau berkeadilan,”tegas Linda Rosalina, Direktur Eksekutif TuK Indonesia yang tergabung dalam Koalisi Forests &Finance.
Laporan itu juga mengidentifikasi nama-nama besar di balik aliran dana global tersebut. JPMorgan Chase, Bank of America, Citi, dan BNP Paribas tercatat sebagai bank penyandang dana terbesar. Di sisi investor, raksasa keuangan seperti BlackRock, Vanguard, dan Capital Group menanamkan miliaran dolar dalam obligasi dan saham perusahaan tambang raksasa dunia, termasuk Glencore, Vale, dan BHP.
Ironisnya, komitmen publik para lembaga keuangan tersebut terhadap keberlanjutan tampak hanya sebatas jargon. Skor rata-rata kebijakan lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) dari 30 lembaga besar yang ditinjau hanya mencapai 22 persen. Banyak perusahaan bahkan tidak memiliki kebijakan dasar untuk mencegah kegagalan pengelolaan limbah, deforestasi, atau perampasan tanah masyarakat adat, padahal sektor tambang dikenal sebagai sektor berisiko tinggi.
“Ini peringatan serius. Tidak mungkin membangun transisi energi yang adil dengan mengorbankan hak asasi, menggusur masyarakat adat, dan menghancurkan keanekaragaman hayati,”ujar Stefani Dowlen dari Rainforest Action Network, salah satu anggota koalisi.
Di Indonesia, sejumlah perusahaan tambang yang beroperasi juga teridentifikasi mendapatkan keuntungan dari aliran pendanaan tersebut. Freeport-McMoRan asal Amerika Serikat tercatat sebagai penerima terbesar dengan nilai hampir USD 22 miliar pada pertengahan 2025. Disusul oleh Zhejiang Huayou Cobalt dari Tiongkok dengan USD 197 juta dan Vale Brasil sebesar USD 77 juta. Dari dalam negeri, Amman Mineral Internasional dan Harita Group juga masuk dalam daftar penerima manfaat pendanaan.
Bank Mandiri menjadi aktor lokal yang disorot karena menduduki posisi pendana terbesar di Indonesia, dengan total kredit mencapai USD 6,4 miliar atau sekitar 20 persen dari total kredit mineral transisi di tanah air. Fakta ini mendorong kampanye #DesakMandiri yang menuntut reformasi mendasar pada arah pembiayaan perbankan nasional.
Kasus Harita Group di Pulau Obi, Maluku Utara, menjadi contoh nyata risiko ekologis dari operasi tambang mineral transisi. Berlokasi di kawasan Segitiga Terumbu Karang, operasional nikel Harita telah mengancam kelestarian terumbu karang dan menghancurkan mata pencaharian nelayan setempat. Aktivitas tambang berbasis tenaga batu bara dan praktik pembuangan limbah (tailing) mencemari sumber air yang vital bagi masyarakat. Meski pencemaran telah lama teridentifikasi sejak 2012, pada 2021 Harita tetap membangun kilang high-pressure acid leaching (HPAL) berskala besar pertama di Indonesia. Proses ini menghasilkan limbah kimia beracun dalam jumlah masif, memicu kekhawatiran besar di kalangan masyarakat sipil. Anehnya, meskipun kritik keras dari JATAM dan Trend Asia terus menguat, Harita justru sukses menghimpun dana segar lewat IPO pada 2023.
Situasi tak jauh berbeda terlihat di Morowali, Sulawesi Tengah, rumah bagi PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), kawasan industri nikel terbesar di Indonesia. Pemantauan TuK Indonesia dan AEER (2023) menemukan kualitas udara di sekitar IMIP tercemar parah. Konsentrasi SO₂, PM2.5, dan PM10 melebihi ambang batas nasional, meningkatkan risiko ISPA, kanker paru, penyakit kardiovaskular, hingga kematian dini. Laporan Forests &Finance bahkan menyebut Tsingshan Group sebagai penerima pendanaan besar melalui kreditur CSC Financial, senilai USD 59,1 juta.
“Fakta bahwa perusahaan seperti Harita dan IMIP masih mendapat dukungan finansial, padahal mereka menghadapi tuduhan pencemaran dan pelanggaran HAM, sungguh mengkhawatirkan,”lanjut Linda Rosalina.
Koalisi Forests &Finance mendesak adanya reformasi mendasar. Mereka menegaskan, transisi energi yang adil hanya bisa tercapai bila sektor keuangan berhenti mendanai perusahaan dengan rekam jejak destruktif. Pemerintah, bank, dan investor didorong untuk menyelaraskan pembiayaan dengan prinsip keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, keberlanjutan lingkungan, serta akuntabilitas penuh dalam rantai pasok.
Pesan utama laporan ini jelas: tanpa perubahan, transisi energi berisiko hanya melanggengkan model eksploitatif yang merusak iklim, alam, dan kehidupan masyarakat. Bukan masa depan hijau yang diwariskan, melainkan krisis baru yang lebih kompleks. (Ali)